“Belajar
dari Kasus Razia Warung di Bulan Puasa”
Sabtu, 11 Juni 2016, saya sempat
membaca sebuah postingan di akun Facebook Fahd Pahdepie yang intinya
mengutarakan kekecewaan terhadap aparat satpol PP yang menutup dan menyita
paksa dagangan seorang ibu pemilik warung. Dalam postingan tersebut, Fahd—jika
boleh saya memanggilnya demikian, mempertanyakan landasan pikir kepala daerah
yang mengeluarkan aturan tersebut, mempertanyakan dasar moral dan dalil agama
yang membenarkan tindakan mereka, serta menuntut keimanan mereka yang—dalam pandangan
Fahd begitu angkuh.
Dalam postingan berbeda, Fahd
kemudian menyodorkan sabda Nabi; Assiyamu
junnatun, artinya puasa adalah perisai. Puasa itu untuk bertahan, bukan
pedang untuk menyerang, tandas Fahd gagah. Maka biarkan saja warung tetap buka,
orang-orang yang tidak berpuasa makan di dekat orang berpuasa, lalu orang yang
berpuasa mengatakan pada diri sendiri: Inni
shaimun, Aku sedang berpuasa. Bukan dengan memaksa mereka “menghormati”
orang yang berpuasa.
 |
| Sumber: Akun Facebook Fahd Pahdepie |
Sepakatkah saya dengan pernyataan
Fahd tersebut? Awalnya iya, bahkan saya sempat membagikan postingan tersebut di
kronologi Facebook saya. Namun setelah membaca postingan “bantahan” dari akun
Facebook Suluh Prasetyo Rendra Utomo (11 Juni 2016), kesepakatan itu berbalik. Dalam
postingan tersebut, Suluh membeberkan sejumlah analisa termasuk fakta di balik
kebijakan penutupan warung pada siang hari oleh pemerintah Serang, Banten.
Pertama, fakta bahwa puasa di
bulan Ramadhan adalah suatu hal yang wajib, sehingga apabila ada udzur yang memaksanya untuk tidak
berpuasa, seorang Muslim wajib menggantinya di hari yang lain atau membayar
kafarat (denda). Kedua, Serang sebagai kota dengan julukan “Kota Santri”
memiliki sekitar 600.000 warga Muslim dan kurang dari 20.000 warga non-Muslim (data 2014). Dalam
perhitungan matematika, perbandingan jumlah orang yang tidak berpuasa (diluar
anak kecil) dibandingkan orang yang berpuasa adalah 1:30. Jika ada dua warung
dalam satu kampung dari sejumlah 60 warga/RT, dimana masing-masing RW terdapat
10 RT, maka masing-masing warung hanya akan memperoleh pembeli maksimal 10
orang saja. Jika modal perhari untuk membuka warung kecil-kecilan sekitar
300-500rb dan warung hanya mampu mendatangkan 10 pembeli dengan asumsi harga
per menu 15ribu, maka warung itu hanya mampu menghasilkan omset maksimal 150ribu
saja. Ini artinya, para pemilik warung menderita rugi minimal separuh dari
modal.
Namun faktanya, omzet justru
meningkat di bulan Ramadhan. Mengapa? Rupanya, ada “konspirasi dosa” antara
pelanggar perintah puasa (pembeli) dengan fasilitator pelanggaran puasa (pemilik
warung). Muslim “tidak taat” inilah yang menjadi pelanggan warung yang buka di
siang hari. Maka demi mencegah kemungkaran itulah pemerintah daerah Serang menerapkan
kebijakan penutupan warung di siang hari. Kebijakan yang dalam pandangan
penulis mengimplementasikan seruan Tuhan: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
Tapi bagaimana dengan nasib para
pemilik warung yang menggantungkan hidupnya dari hasil berjualan di warung
kecil-kecilan tersebut? Masih dalam postingan yang sama, Salim menjawabnya
dalam poin ke-12. Menurut Salim, warung tidak harus ditutup seharian penuh,
melainkan hanya di jam-jam orang berpuasa saja (Subuh hingga Maghrib). Sementara
di jam berbuka hingga sahur, mereka tetap bisa berjualan. Bahkan kemungkinan
besar lebih laris dibandingkan hari-hari di luar Ramadhan. Inilah berkah Ramadhan
yang sesungguhnya, meraup asa di jalur yang tak mengganggu kekhusyukan orang
beribadah.
Bentuk toleransi serupa untuk
menjaga kekhusyukan orang beribadah juga diberlakukan pada perayaan Nyepi di
Bali. Pada saat pelaksanaan Catur Brata Penyepian, ketua adat Bali menerapkan
kebijakan pemberhentian semua aktivitas di Bali termasuk penerbangan pesawat,
kapal laut, angkutan darat, pelarangan penduduk atau wisatawan keluar dari
rumah/penginapan, larangan membuat kegaduhan, hingga pelarangan aktivitas memasak
dan menghidupkan listrik.
 |
| www.disparda.baliprov.go.id |
Apakah ini berarti semua orang di
Bali beragama Hindu dan merayakan Nyepi? Tentu saja tidak. Meskipun menjadi
agama mayoritas, tidak semua orang di Bali beragama Hindu. Namun umat non-Hindu
di Bali menghormati peribadatan Nyepi dan mematuhi sejumlah aturan yang berlaku
di sana. Jika melanggar, bersiaplah untuk menerima hukuman adat dan denda.
Jika semua aktivitas
diberhentikan, bagaimana aktivitas perekonomian di Bali? Apakah menurun? Tidak.
Justru menaik. Hal ini karena diluar pelaksanaan Catur Brata Penyepian,
terdapat Festival Ogoh-ogoh yang justru menjadi daya tarik wisatawan untuk
berkunjung ke Bali. Maka jangan heran apabila sebelum pelaksanaan Catur Brata
Penyepian, penerbangan di Bali menjadi ramai, reservasi hotel meningkat dan supermarket
sesak oleh warga yang berbelanja guna mempersiapkan segala hal menyambut Catur
Brata Penyepian.
Hal serupa juga berlaku di momen
Ramadhan. Menjelang Ramadhan, supermarket sesak oleh warga yang mempersiapkan
kebutuhan saur dan berbuka, begitupun banyak warga yang menjadi penjual dadakan
aneka menu berbuka puasa, kerudung, baju Muslim dan sebagainya. Momen peribadatan
senantiasa menjadi berkah bukan hanya bagi pengusaha berskala besar, melainkan
juga pedagang kecil bahkan rakyat biasa.
Meskipun serupa, mengapa pemberhentian
aktivitas di Bali pada momen Nyepi tidak memicu perdebatan? Mengapa ketua adat
Bali tidak mendapat kecaman selayaknya pemerintah daerah di Serang?
Inilah hebatnya media massa
menggiring opini publik sehingga seolah-olah ada rakyat kecil yang tertindas
oleh kebijakan tertentu pemerintah. Padahal kebijakan tersebut sudah lama
diterapkan dan tidak pernah diperdebatkan. Naasnya, media sosial membuat opini menyebar
sedemikian cepatnya sehingga memicu beragam reaksi publik dunia maya. Interpretasi
dangkal yang diungkapkan dalam postingan Facebook dengan menyudutkan aturan
berbau syariat kian menguatkan opini bahwa Islam adalah agama yang intoleran,
angkuh, dan “sok kuasa”. Ini berbahaya bagi sebagian orang yang masih awam
tentang Islam sehingga berpotensi besar memicu konflik antar agama, bahkan
konflik intern Islam dengan mengkafirkan aliran-aliran Islam tertentu.
 |
| Sumber: Fanspage Media Aswaja |
Apakah ini berarti media sosial adalah “biang
kerok” atas kasus ini? Sama sekali tidak.
Facebook, sama halnya dengan
media sosial lainnya, pada dasarnya bersifat netral. Dia bisa menjadi tempat
menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama, begitupun efektif dalam
membunuh rasa toleransi tersebut. Tinggal bagaimana kita mengisi “ruang kosongnya”
agar tidak terkesan tendensius sehingga menggiring ke konflik berbau SARA. Salah
satunya dengan memposting informasi positif mengenai keberagaman pelaksanaan
peribadatan di setiap daerah di Indonesia. Beberapa contohnya bisa dilihat di
akun Twitter @SebangsaID dan Instagram @Icrs_Yogya.
Pada
akhirnya, semoga kita bisa lebih bijak dalam menanggapi sebuah berita di media
massa dan tak gegabah untuk menyebarkan interpretasi kita di media sosial. Sebab
“bersuara” di media sosial sama saja dengan berbicara di mimbar dunia. Siapapun
bisa “mendengar” suaramu, dan siapapun bisa terpancing oleh “omonganmu”. Jangan
sampai, “suara” kita menjadi penyebab robohnya dinding persaudaraan antar umat
beragama.
“artikel ini
diikutsertakan dalam Kompetisi Blog yang diselenggarakan oleh ICRS dan Sebangsa”

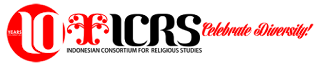
Komentar
Posting Komentar